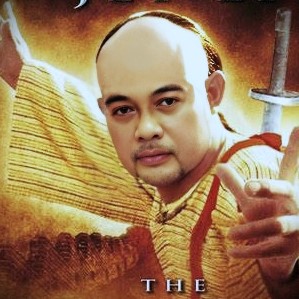Menjawab pertanyaan yang kerap diajukan kepada saya tentang rencana revisi Undang-undang Penyiaran oleh Komisi I DPR RI tahun 2024.
1. Bagaimana pendapat Anda ttg draft revisi UU Penyiaran yang saat ini sedang ramai dicuitkan di medsos?
Saya dengan tegas menolak draft revisi UU Penyiaran yang saat ini juga menuai penolakan dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Penolakan ini didasarkan pada beberapa landasan berpikir yang kuat:
Pertama, Melanggar Prinsip Kebebasan Berekspresi dan Pers:
Salah satu pilar fundamental demokrasi adalah kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Revisi UU Penyiaran nampaknya akan membatasi ruang jurnalisme investigasi, kritik sosial, dan karya jurnalistik lainnya yang kritis terhadap kekuasaan.
Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial.
Dalam banyak pasal juga ditemukan prinsip sensor konten, ancaman pencemaran nama baik, larangan konten fitnah yang tidak jelas ukurannya, yang ditengarai menyasar produk media digital.
Kedua, Menghambat Arus Informasi dan Keberagaman Media:
Draft revisi ini dikhawatirkan akan membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang beragam dan berkualitas. Ketentuan yang menambahkan perizinan untuk konten siaran selain isi siaran, dapat menghambat arus informasi dan pertukaran budaya.
Selain itu, sanksi denda yang tinggi dan potensi pencabutan izin usaha dikhawatirkan dapat melemahkan media kecil dan menciptakan monopoli media oleh perusahaan besar.
Ketiga, Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi:
Proses revisi UU ini amat terbatas akuntabilitas dan transparansinya. Kurangnya partisipasi publik yang bermakna dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas dan legitimasi proses revisi.
Keempat, Potensi Penyalahgunaan Kewenangan:
Pemberian kewenangan tambahan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi konten siaran berpotensi disalahgunakan demi kepentingan tertentu, apalagi masa jabatan komisioner KPI digadang-gadang menjadi 5 tahun.
Jadi revisi UU Penyiaran yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik dan berpotensi melanggar hak asasi manusia harus ditolak. Penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi dalam merumuskan regulasi penyiaran yang adil, terbuka, dan akuntabel.
DPR dan pemerintah harus menunda pengesahan revisi UU Penyiaran dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk masa depan penyiaran di Indonesia.
2. Kalau draft revisi UU dianggap tidak jelas, basic pasal2 yg oleh banyak kelompok masyarakat ditolak itu, sumbernya dr draft yg mana?
Saya memperoleh draft dari teman-teman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Bulan April 2024 lalu. Publik tidak dapat dengan mudah memperoleh draft revisi itu langsung dari DPR. Ini bukti proses pembentukan hukum di gedung parlemen perlu terus diperbaiki agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat demokratis yang trasparan dan akuntabel.
3. Pasal2 yang dianggap memberatkan dan kenapa? Implikasinya apa?
Karena draft RUU-nya dianggap tidak akurat maka saya menghindari penyebutan pasal-pasal melainkan prinsip-prinsipnya saja.
Pertama-tama, dalam draft revisi uu penyiaran itu ada banyak kerancuan definisi atau ketentuan umum.
Misalnya, definisi penyiaran, itu tidak jelas. Menurut ketentuan umum dalam draft revisi undang-undang penyiaran:
"Penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal Siaran dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, internet, atau sistem transmisi lainnya, atau dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk dapat diterima secara bersamaan dan/atau dapat diakses kembali oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran."
Ini definisi yang tidak definitif. Yang baca ini akan bingung sendiri, yang disebut penyiaran itu apa? Ini palugada. Maksa, agar bisa mencakup media baru. Di kalangan akademisi saja, istilah media baru masih ambigu apalagi jika ditambah kata "tindakan mentransmisikan sinyal". Sebab ambil contoh, saya yang punya akun Youtube, tidak ikut mentransmisikan sinyal, karena itu dilakukan Google.
Kedua, soal siapa pelaku yang jadi objek undang-undang. dalam definisinya, disebut tiga kategori, tetapi pada prinsipnya, siapa saja nanti akan diawasi. luarbiasa. Palugada.
Berikut definisi pelaku penyiaran menurut draft revisi uu penyiaran itu:
"Lembaga Penyiaran adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Penyiaran dengan memproduksi dan memancarluaskan siaran secara teratur dan berkesinambungan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital".
Selain lembaga penyiaran, juga ada pelaku lain yang diawasi, yaitu:
"Penyelenggara Platform Digital Penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan atau lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui Platform Digital Penyiaran."
serta:
"Penyedia isi siaran adalah pihak yang memproduksi dan menyampaikan isi siaran kepada Lembaga Penyiaran."
Ketiga, kerancuan soal apa yang diawasi. ada dua istilah ambigu, yaitu: "isi siaran" dan "konten siaran".
Berikut definisi keduanya menurut draft revisi uu penyiaran.
"Isi Siaran adalah Siaran yang diproduksi oleh lembaga Penyiaran."
lalu,
"Konten Siaran adalah materi Siaran digital yang diproduksi oleh Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau penyelenggara platform teknologi Penyiaran lainnya."
Jadi, sekali lagi ada dua objek pengawasan, isi siaran dan konten siaran, yang ternyata berbeda pelaku.
Itu barusan tentang "objek kegiatan yang diawasi" oleh undang-undang.
Definisi rancu lain adalah istilah-istilah kunci, seperti "konten berbahaya" atau "kepentingan publik", bisa menjadi celah untuk membatasi konten yang tidak sesuai kepentingan pihak tertentu.
Keempat, tujuan penyiaran yang mengikat semua pihak yang diatur, salah satunya yaitu:
"pasal 3 poin d. meningkatkan harkat, martabat, dan citra bangsa;"
Implikasinya, seluruh isi dan konten siaran harus jadi humas-nya negara gitu ya? Ga boleh menurunkan citra.
Waah masih banyaaakkk.. itu baru sampe pasal 3.. sementara draft ini berisi ratusan pasal nih.. Semoga publik juga peduli karena akan menjadi konsumen media.
Ambil sedikit contoh lain yaa.. yaitu pasal tentang Lembaga Penyiaran Publik.
Pada bagian ini lembaga penyiaran publik (LPP) wajib menyiarkan program pemerintah. Pasal begini jelas membatasi independensi LPP dan mengubahnya menjadi alat propaganda pemerintah.
Implikasinya:
Hilangnya kepercayaan publik terhadap LPP sebagai sumber informasi yang objektif dan netral.
Terkikisnya nilai demokrasi karena LPP tidak lagi menjadi ruang publik untuk diskursus dan kritik terhadap pemerintah.
Selanjutnya bagian Pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran UU Penyiaran juga bermasalah. Sanksi denda yang tinggi dan potensi pencabutan izin usaha tanpa proses pengadilan, dikhawatirkan dapat melemahkan keberagaman isi media dan memukul media kecil.
Implikasinya, terpeliharanya monopoli media oleh perusahaan besar yang memiliki modal kuat.
Hilangnya suara-suara kritis dari media atau content creator yang berani menyuarakan kepentingan rakyat.
Pasal lain yang bermasalah adalah memberi tugas tambahan kepada KPI yaitu pengawasan terhadap media digital. Ketentuan yang memberikan kewenangan besar kepada KPI untuk mengawasi konten siaran dikhawatirkan dapat melanggar privasi pengguna dan mematikan ruang ekspresi di media sosial.
Implikasinya, tercipta budaya takut bicara di kalangan pengguna media sosial. Bukan budaya beradab dalam bicara di media sosial. Serta matinya ruang publik digital sebagai wadah untuk bertukar informasi dan gagasan.
Ada lagi soal pelarangan Konten tertentu, seperti jurnalisme investigatif. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan bertentangan dengan UU40/99 tentang Pers, yang menyebut tidak ada pelarangan penyiaran, tidak ada sensor dalam kegiatan jurnalistik. Belum lagi pasal yang menyebut KPI juga menangani sengketa jurnalitik dalam penyiaran. Jelas bertentang dengan UU 40/99 yang menyebut sengketa pers diselesaikan hanya oleh dewan pers. Implikasinya, ketidakjelasan regulasi dan potensi konflik antar lembaga terkait pengaturan media.
Pasal-pasal tambahan ini perlu dikaji ulang karena berpotensi membatasi kreativitas, melemahkan fungsi kontrol media, dan menciptakan ketidakpastian hukum.
Penting untuk memastikan revisi UU Penyiaran ini mengedepankan kebebasan berekspresi, regulasi yang jelas dan proporsional, serta ekosistem media yang sehat dan demokratis.
4. Harapan ke depan soal penyusunan RUU Penyiaran ini seperti apa?
Saya berharap parlemen tunduk dan berpedoman pada peraturan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak otoriter, melainkan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai perintah mahkamah konstitusi.
5. Poin Utama
Saya sorot kembali beberapa poin penting :
1. Potensi Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Pers:
Beberapa pasal dalam draft revisi dikhawatirkan dapat membatasi ruang jurnalisme investigasi dan kebebasan berekspresi. Saya menekankan pentingnya menjaga kebebasan berekspresi dan pers. Revisi UU Penyiaran seyogyanya tidak boleh melanggar hak asasi manusia ini dan justru harus memperkuat budaya demokrasi di Indonesia. Kekuatiran terhadap konten media digital yang bebas mengalir tidak bisa dititipkan ke dalam Undang-undang Penyiaran.
2. Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi:
Dunia penyiaran telah berkembang pesat dengan kemunculan platform digital dan media baru. UU Penyiaran yang direvisi perlu adaptif dengan perkembangan ini agar dapat mengatur semua jenis lembaga penyiaran dan media secara adil dan merata. Penting untuk memastikan keberagaman informasi dan konten yang berkualitas bagi masyarakat. Bukan fokus pada kewenangan tapi pelayanan. Sementara kekuatirana terhadap konten di media digital, pemerintah cukup menghadapi pengelola platform media digital dan bukan mengurusi users (pengguna) atau content creator satu persatu.
3. Penguatan KPI:
Banyak pihak mendukung penguatan peran KPI untuk meningkatkan kualitas siaran dan melindungi masyarakat dari isi siaran yang tidak sejalan dengan tujuan penyiaran nasional.
Namun, perlu dipastikan bahwa kewenangan KPI tidak tumpang tindih dengan lembaga lain, seperti Dewan Pers, dan akuntabilitasnya kepada publik diperkuat.
Keseimbangan antara otoritas dan akuntabilitas KPI sangat penting untuk memastikan regulasi penyiaran yang efektif dan demokratis. Kaitkan kembali antara tugas pengawasan dengan kewenangan perijinan oleh KPI yang dihapus UU Omninbus..
4. Partisipasi Publik:
Proses revisi UU Penyiaran harus terbuka dan transparan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pakar media.
Revisi UU Penyiaran merupakan langkah penting untuk merespon perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Namun, revisi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan yang terkait.
Saya berharap revisi UU Penyiaran ini dapat menghasilkan regulasi yang adaptif, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penting untuk mengedepankan prinsip kebebasan berekspresi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses revisi ini.
============
Nursyawal, M.I.Kom., kandidat doktor bidang komunikasi sains, pengajar jurnalistik dan penyiaran, mantan komisioner kpid jabar, anggota AJI Indonesia, aktif juga di CSO bernama KNRP ( koalisi nasional untuk reformasi penyiaran).